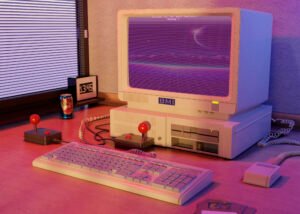Semenjak kebijakan inklusif yang diterapkan oleh pemerintahan di Era Reformasi, Indonesia dinilai telah bersifat akomodatif terhadap etnis Tionghoa yang sebelumnya merupakan kelompok terepresi (oppressed minority) di masa Orde Baru. Beberapa akademisi dan sejarawan seperti Wibowo dan Thung (2010) menilai posisi etnis Tionghoa di Indonesia pasca-1998 sudah relatif terintegrasi dalam identitas nasional Republik Indonesia.
Integrasi Tionghoa dalam identitas kebangsaan Indonesia dicerminkan antara lain dengan pengakuan agama Konghucu, tradisi Barongsai, perayaan Imlek, dan bahkan komunitas Tionghoa sendiri sebagai salah satu suku bangsa Indonesia. Bahkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 mencabut penggunaan istilah “China” dan “Cina” untuk Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa dengan alasan konotasi diskriminatif. Seluruh perkembangan positif tersebut seakan-akan semakin memantapkan integrasi Tionghoa dalam identitas NKRI serta memudarkan stereotip bahwa mereka adalah “suku asing”.
Meski demikian, data deskriptif dari Google Trends justru menunjukkan, sejak tahun 2014 ada peningkatan signifikan dalam tren pencarian kata-kata yang mengangkat identitas “asing” WNI keturunan Tionghoa. Pencarian Google Trend ini difokuskan pada kata-kata yang mengekspolitasi identitas keturunan asing etnis Tionghoa serta kerap diungkapkan oleh tokoh publik, antara lain “Aseng” dan “TKA Cina”.
Oleh karena itu, cercaan berbasis kesukuan (ethnic slurs) seperti “Cokin”, “Cino”, ataupun “Singkek” tidak digunakan dalam analisis data ini, karena istilah-istilah ini tidak terfokus pada “ke-asing-an” Tionghoa. “Aseng” sejatinya adalah nama laki-laki Tionghoa, namun kerap dipelesetkan maknanya untuk menyerang identitas WNI keturunan Tionghoa karena terdengar seperti kata “asing”. Sementara itu, “TKA Cina” merujuk pada kontroversi kedatangan tenaga kerja asing asal Republik Rakyat Cina (RRC). Namun kata TKA Cina kerap digunakan dalam forum online sebagai justifikasi kebencian terhadap WNI keturunan Tionghoa yang sama sekali bukan warga negara RRC.
Grafik di bawah menunjukkan visualisasi popularitas online kata “Aseng” meningkat seiring dengan politisasi identitas etnis pada Pemilihan Presiden 2014. Situs berita Deutsche Welle Indonesia lebih lanjut melaporkan adanya serangan kesukuan ditujukan terhadap salah satu calon yang dinilai memiliki hubungan erat dengan etnis Tionghoa.
Kata “Aseng” pun kembali populer di masa Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di mana salah satu calon gubernurnya beretnis Tionghoa. Demikian pula dengan laporan Liputan 6 bahwa Pemilihan Presiden 2019 membuat popularitas kata “TKA Cina” melejit dengan konteks menyerang kelompok politik tertentu.
Google Trend menunjukkan bahwa trend pencarian kata-kata seperti “Aseng” dan “TKA Cina” meningkat dalam kontestasi politik tingkat tinggi
Jika dilakukan perincian berdasarkan provinsi, kata “Aseng” menjadi sebuah tren di seluruh provinsi di Pulau Jawa plus Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, serta Sulawesi Selatan. Sementara itu, kata “TKA Cina” cenderung menjadi tren di Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Secara demografi dan politik, terdapat alasan mengapa wilayah-wilayah di atas menjadi pusat dari penggunaan kata-kata bernada rasis terhadap etnis Tionghoa. Visualisasi grafik berikut yang diolah Litbang Kompas/ERN berdasarkan Sensus Penduduk 2010 menyimpulkan korelasi provinsi dengan tren kata “Aseng” atau “TKA Cina”, yakni sebagai provinsi yang memiliki populasi Tionghoa terbesar secara nasional. Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau terlihat masuk dalam kategori ini.
Data yang dilansir Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2019 juga melaporkan, provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat memiliki tingkat toleransi yang cenderung rendah. Kedua provinsi tersebut bersama Riau dan NTB masuk ke dalam peringkat 10 besar provinsi dengan toleransi paling rendah di Indonesia. Rendahnya tingkat toleransi ini rentan dimanfaatkan oleh pihak provokator untuk menyebarkan ujaran kebencian terhadap Tionghoa secara online.
Selain itu, Pulau Jawa dikenal sebagai pusat kontestasi politik dalam skala nasional. Fenomena ini menjelaskan meskipun provinsi-provinsi di pulau Jawa seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak tergolong ke dalam provinsi dengan skor toleransi yang rendah, namun diskursus online tentang politik identitas, seperti ke-asing-an Tionghoa, menjadi tren akibat peran Jawa sebagai pusat kontestasi politik nasional (Fachrudin, 2019).
Skema di bawah ini menggambarkan bagaimana unggahan di platform media sosial seperti YouTube, Twitter dan Facebook kerap menjadi sarana yang efisien dalam membakar sentimen rasisme. Pengguna media sosial, baik yang menggunakan identitas asli atau anonim, dapat mengunggah berbagai macam ujaran kebencian secara leluasa.
Hal ini turut diperparah dengan minimnya algoritma media sosial untuk menyaring berbagai ekspresi ujaran kebencian dalam Bahasa Indonesia serta konteks sosial-politik Indonesia. Saat ini pun otoritas di Indonesia belum memiliki cara yang efisien dan praktis untuk menjaring ujaran kebencian. Setelah unggahan tersebut dilihat (viewed) oleh berbagai pihak, dampak yang dapat dipicu adalah konflik yang terjadi dalam dunia nyata. Demonstrasi bernada suku, agama, dan ras (SARA), penyerangan terhadap pemuda Tionghoa, atau kerusuhan di sebuah kota kecil terjadi akibat unggahan online.
Setidaknya ada dua alasan mengapa internet menjadi sebuah lahan subur untuk sentimen anti-Tionghoa, yakni tidak adanya regulasi mengenai ujaran kebencian online, serta fungsi media sosial sebagai sarana mobilisasi politik yang efisien berbasis ujaran kebencian.
Minimnya Pengawasan Siber
Wibowo (2018) berargumen, media sosial seperti Twitter dan Facebook menjanjikan sebuah anonimitas bagi penggunanya. Anonomitas inilah yang digunakan pihak penyebar ujaran kebencian sebagai tameng untuk menyuarakan opini kontroversional di internet yang berfungsi sebagai public sphere (ruang publik). Meskipun pemerintah sudah memiliki UU ITE pasal 27 ayat 3 untuk menjerat pelaku ujaran kebencian online, definisi pasal tersebut dinilai bersifat multitafsir dalam mendefinisikan “ujaran kebencian online”. Dengan kata lain, UU ITE pasal 27 ayat 3 kerap dilihat oleh beberapa pakar sebagai sebuah “pasal karet” yang tidak efisien melihat ujaran kebencian yang dapat didefinisikan secara berbeda-beda.
Lemahnya kemampuan UU ITE dalam menuntut kasus ujaran kebencian online memberanikan beberapa tokoh publik untuk menyuarakan sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Salah satu kasus paling terkenal adalah klaim Buni Yani bahwa tuduhan ujaran kebencian berbau SARA hanyalah sebuah misinterpretasi lawan politiknya (BBC Indonesia, 2016).
Indonesia pun belum memiliki sistem algoritma efisien yang bisa menyaring ujaran kebencian, ataupun data mining yang efektif dalam menjaring ujaran kebencian secara otomatis di media sosial dan konteks Indonesia dengan Bahasa Indonesia (Putra et. al., 2018). Pelaporan ujaran kebencian masih sangat tergantung pada pelaporan warganet secara manual kepada pihak yang berwenang, seperti Divisi Siber Polri (Fatahillah et. al., 2017)
Algoritma Twitter Bahasa Indonesia juga belum begitu efisien dalam menjaring unggahan yang bernada diskriminatif. Hal ini berbeda dengan algoritma yang cenderung lebih efisien dalam konteks negara Barat dan Bahasa Inggris. Laporan CNBC pada 2020 melansir, ujaran kebencian bernada rasis yang muncul membabi buta pada masa Pemilihan Presiden 2019 Amerika Serikat ditanggapi secara cepat oleh Twitter dan Facebook tanpa harus menunggu adanya pelaporan secara manual oleh warganet, seperti yang dicontohkan oleh potongan berita berikut mengenai situs alt-right (ekstremis Sayap Kanan di AS).
Wahana Gerakan Politik
Ujaran kebencian terhadap WNI keturunan Tionghoa berkembang secara online karena berbagai platform media sosial adalah sarana mobilisasi politik yang efisien. Etnis Tionghoa kerap menjadi “kambing hitam” kondisi perekonomian Indonesia dalam kampanye politik, bahkan di Era Reformasi sekalipun (Sahrasad, 2019).
Unggahan online dengan konsep Tionghoa sebagai entitas “asing” yang menjadi biang keladi permasalahan ekonomi dalam negeri masih menjadi hal yang cukup mudah untuk ditemui. Beberapa contoh topik online tersebut seperti monopoli ekonomi konglomerat keturunan Tionghoa yang menimbun kekayaan mereka di luar negeri, masuknya TKA dari RRC, dan lain-lain.
Narasi Tionghoa sebagai kambing hitam asing pada akhirnya kerap menjadi justifikasi tindakan diskriminatif terhadap WNI keturunan Tionghoa. Sahrasad (2019) melanjutkan, taktik yang digunakan pada Orde Baru ini masih dilakukan di masa Reformasi sekarang. Hal ini dapat dilihat dari Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, cuitan dan unggahan tentang latar belakang etnis salah seorang calon dari etnis Tionghoa mengalahkannya secara telak.
Seperti halnya dengan faktor pertama, upaya mengkambinghitamkan etnis Tionghoa sebagai ujaran kebencian ini juga dikarenakan tidak adanya upaya preventif dalam menyaring ekspresi beropini di ranah digital Indonesia. Oleh karena itu, kiranya pihak yang berwenang perlu untuk bekerja sama dengan akademisi untuk dapat mengimplementasikan algoritma yang efisien untuk membendung ujaran kebencian demi persatuan bangsa.
Referensi
BBC Indonesia (2016). https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38093502
Deutsche Welle Indonesia (2014). https://www.dw.com/id/jokowi-digempur-kampanye-fitnah/a-17758807
Fatahillah, N. R., Suryati, P., Haryawan, C. (2017). Implementation of Naive Bayes classifier algorithm on social media (Twitter) to the teaching of Indonesian hate speech, 2017 International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology (SIET)
Putra, B.P., Irawan, B., & Setianingsih, C. (2018). Deteksi ujaran kebencian dengan menggunakan algoritma Convolutional Neural Network pada gambar. e-Proceeding of Engineering, 5(2), 55-65.
Sahrasad, H. (2019). Colonial structure, Chinese minority and racial violence in Indonesia: A social reflection, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 2(2), 209-221.
Wibowo, I. & Thung J.L. (2010). Setelah air mata kering: Masyarakat Tionghoa pasca-peristiwa Mei 1998. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Wibowo, T.O. (2018). Konstruksi ujaran kebencian melalui status media sosial. Channel Jurnal Komunikasi, 6(2), 169-176.
Liputan 6 (2019). https://www.liputan6.com/bisnis/read/3917854/tka-china-hingga-honorer-3-isu-soal-pekerja-jelang-pilpres
Related Post

Kenyamanan Berbagi Momen Pribadi di Ruang Virtual
August 22, 2023/Read More

Forum Gosip Daring: Bagai Pedang Bermata Dua
August 22, 2023/Read More